Memasuki bulan Mei, ingatan kolektif kita langsung tertuju pada kerusuhan 13-15 Mei ’98 yang merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Ya, kita menolak lupa akan luka sejarah bangsa yang masih menganga.
Kita akan mencoba meresensi sebuah novel grafis ‘Chinese Whispers’ dan mengingat kembali koyakan sejarah kerusuhan Mei ’98 melalui lorong labirin yang dicipta oleh Rani Pramesti. Novel grafis ini telah dirilis tahun 2014 di Melbourne International Fringe Festivals. Awalnya proyek yang dikerjakan Rani ini merupakan labirin sensoris, namun kini telah bertransformasi menjadi novel grafis dalam versi bahasa Indonesia dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
Rani Pramesti adalah seorang seniman keturunan Cina, Jawa dan Australia yang mencoba keluar dari kebingungan jati dirinya. Komik ini adalah tanggapan Rani pribadi terhadap kerusuhan ’98 yang dia alami sendiri serta berdasarkan cerita-cerita perempuan keturunan Tionghoa lainnya yang ia temui dan wawancarai di Australia.
Saat kerusuhan ’98 terjadi 21 tahun yang lalu, ia masih berumur 12 tahun. Ia dan keluarganya beruntung karena selamat dari amuk massa. Namun, menurut berbagai sumber ada sekitar 1.200 orang yang terbunuh dan ratusan perempuan etnis Tionghoa yang diperkosa saat kerusuhan tersebut terjadi. Rani dan keluarganya kemudian pindah ke Australia.
Kerusuhan Mei ’98 bisa saja telah berlalu, namun kenangan terkait kekerasan, ketegangan rasial dan trauma kelam sejarah belum juga hilang dari ingatan penulisnya. Melalui Chinese Whispers ini penulis novel grafis ini mencoba menyembuhkan diri dari kejadian-kejadian traumatis akibat kerusuhan Mei ’98.
Dalam karya ini, penulis ingin menunjukkan sebuah bentuk rasisme bermotivasi politik yang dampaknya sangat kompleks, yaitu adanya kebencian yang diarahkan kepada orang Indonesia keturunan Tionghoa. Kebencian rasis tersebut membuat Rani membenci dirinya sendiri. Itulah sebabnya di salah satu bab Chinese Whispers ada yang berjudul “Mewarisi Kebencian.”
Tidak hanya kebencian orang terhadap orang Indonesia keturunan Tionghoa yang disorot, namun juga menyorot adanya kebencian rasial orang keturunan Tionghoa terhadap orang pribumi. Ketika menelusuri jejak sejarah, kita menemukan bahwa kerusuhan Mei ’98 hanyalah sebagian kecil dari sentimen anti-Cina yang sudah lama dipupuk. Sentimen yang sama juga tumbuh dari politik segregasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda saat menjajah Indonesia. Ini menjadi kerangka politis dan historis untuk memahami kerusuhan Mei ’98.
Ada segregasi inter-rasial dan kecurigaan antar ras, serta kebencian interpersonal yang dimanfaatkan pada Mei ’98. Sampai sekarang kita masih menghadapi upaya penyangkalan fakta sejarah karena masih ada yang percaya bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa pada saat kejadian kerusuhan Mei ’98 tak pernah terjadi. Masih banyak yang bungkam, penyangkalan dan usaha menutup-nutupi fakta. Bahkan, kasus ini sama sekali tidak berusaha diselesaikan.
Impunitas adalah musuh terbesar dari proses penyembuhan, sehingga penulis sepakat dengan pertanyaan sejarawan dan penulis sejarah Indonesia Max Leigh, “Apa bisa kamu menyembuhkan trauma tanpa mendapat keadilan?”
Novel grafis ini tidak ingin mengklaim akan mampu menyembuhkan luka bangsa ini, tetapi setidaknya kita sebagai anak bangsa tak akan tinggal diam. Mengakui kepedihan yang dialami para korban sebagai bagian dari upaya penyembuhan trauma. Negara seharusnya tidak tinggal diam dan membiarkan para korban memulihkan dirinya sendiri.
Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Rani Pramesti, Komnas Perempuan telah menurunkan Temuan TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Publikasi temuan TGPF ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan Komnas Perempuan atas adanya pihak-pihak yang terus meragukan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan menagih tanggung jawab negara.
Silakan unduh ‘Chinese Whispers’ di link ini: https://thechinesewhispers.com/
Siti Rubaidah




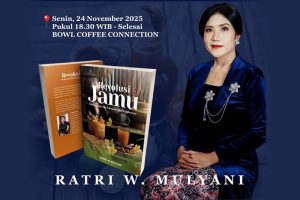
Terkait
Surat kepada Perempuan Pembela HAM yang Dipenjara
Perempuan Pembela HAM, Terdepan Berjuang untuk Keadilan di Tengah Ancaman yang Meningkat
PBB Bersiap Memilih Sekjend Baru, Kepemimpinan Perempuan Jadi Harapan