Dunia terus berubah, kesempatan bagi perempuan untuk maju dan memasuki ruang-ruang publik semakin terbuka lebar. Namun demikian, peluang perempuan untuk menduduki posisi strategis di dunia kerja, organisasi maupun partai politik masih mengalami hambatan. Hambatan atau penghalang apa yang membuat perempuan susah naik ke level yang lebih tinggi? Ada fenomena glass ceiling yang menjadi salah satu penyebab utamanya.
Fenomena ini perlu menjadi perhatian karena merupakan bentuk diskriminasi halus tetapi merugikan, karena seseorang tidak bisa menempati posisi yang lebih tinggi bukan karena tidak mampu, tidak memiliki keterampilan atau tidak berusaha lebih keras. Misalnya, anggapan bahwa perempuan lebih cocok bekerja atau mengurus hal-hal administratif karena perempuan lebih perasa, rapi dan telaten. Oleh karena itu perempuan sering ditempatkan di posisi yang membutuhkan penampilan saja dan bukan sebagai pengambil kebijakan. Selain itu terdapat berbagai bentuk diskriminasi di tempat kerja, seperti dalam hal gaji dan kesempatan kerja yang bisa mengurangi motivasi mereka dalam bekerja.
Menurut data UN Women, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki di seluruh dunia. Hal bisa dilihat pada partisipasi laki-laki di usia angkatan kerja 25-54 tahun sebesar 94 persen, sedangkan partisipasi perempuan hanyalah 63 persen (ILO, 2018). Sedangkan, partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan sebesar 52,6% sedangkan laki-laki 81,4%.
Berdasarkan databoks yang dirilis oleh Katadata, 2,82 juta pekerja di jabatan manajerial, sebanyak 33,08% merupakan perempuan. Jumlah itu meningkat 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 30,37%. Meski demikian, proporsi perempuan pada posisi manajerial masih tertinggal dari laki-laki yang sebesar 66,2% (BPS, 2020).
Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di dunia tenaga. Di sisi lain, meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang menduduki posisi manajerial, namun proporsinya masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Padahal kedudukan perempuan dalam posisi manajerial tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka mampu berpartisipasi penuh serta punya kesempatan kepemimpinan yang sama dalam pekerjaan. Artinya, meskipun ada kemajuan namun masih ada hambatan bagi perempuan untuk menembus langit-langit kaca.
Apa itu Glass Ceiling?
Apa itu glass ceiling? Menurut definisi Investopedia, glass ceiling is an invisible systemic barrier that prevents certain people from rising to senior-level positions within an organization. Glass Ceiling atau langit-langit kaca adalah hambatan sistemik yang tidak terlihat yang mencegah orang tertentu untuk mencapai posisi senior dalam suatu organisasi.
Glass ceiling adalah penghalang yang mencegah orang berkualifikasi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam suatu organisasi, seringkali karena diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau etnis. Hambatan ini seringkali tidak terlihat, namun jelas dalam praktik perekrutan, promosi, dan keputusan penting lainnya. Budaya yang menempatkan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan yang menjadi sebab lahirnya fenomena glass ceiling ini.
Glass ceiling adalah istilah yang menggambarkan adanya hambatan atau penghambat yang tidak terlihat tetapi mutlak, yang dapat mencegah perempuan untuk menduduki posisi tinggi di tempat kerja. Glass Ceiling merupakan ungkapan metafora untuk menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan kaum minoritas saat mencoba peran yang lebih tinggi dan dalam perusahaan. Meskipun banyak perempuan mempunyai kualifikasi dan kemampuan yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan laki-laki namun mereka kesulitan menembus batasan ini.
Kapan Istilah ini Muncul?
Kapan istilah ini muncul? Istilah glass ceiling atau langit-langit kaca pertama kali diperkenalkan oleh Marylin Loden pada tahun 1978. Ia menjelaskan bahwa perempuan sangat sulit atau bahkan kerap tidak bisa menduduki posisi manajerial. Istilah glass ceiling ini sebenarnya tidak hanya merujuk pada perempuan di tempat kerja, tetapi juga kelompok minoritas lainnya, seperti kaum disabilitas dan kulit hitam.
Istilah glass ceiling menjadi lebih dikenal dan digunakan secara luas pada tahun 1980-an, terutama berkat karya Gay Bryant dan publikasi seperti AdWeek dan Wall Street Journal. Istilah ini mulai populer di media dan politik, misalnya ketika Geraldine Ferraro dicalonkan sebagai calon wakil presiden AS pada tahun 1984.
Tahun 1993, istilah glass ceiling mulai masuk dalam kamus Merriam-Webster Collegiate Dictionary dan lebih dikenal secara luas. Saat ini, meskipun ada kemajuan dalam keberagaman di tempat kerja, glass ceiling masih menjadi isu yang relevan, terutama bagi perempuan.
Apakah Glass Ceiling bisa ditembus? Ada banyak contoh glass ceiling yang berhasil ditembus oleh individu. Perempuan yang duduk di Parlemen, perempuan kepala daerah dan perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan adalah contoh perempuan yang mampu menembus langit-langit kaca.
Kita tahu bahwa sejak pemilihan presiden AS pertama pada tahun 1789 hingga awal abad ke-21, tidak ada orang kulit hitam yang menjabat sebagai presiden. Baru setelah disahkannya Voting Rights Act tahun 1965, semua orang kulit hitam dapat memilih. Pada tahun 2008, Barack Obama menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Barack Obama adalah contoh orang dari kaum minoritas Afrika-Amerika pertama yang mampu menembus glass ceiling.
Sedangkan Kamala Harris memecahkan glass ceiling ketika ia menjadi wakil presiden perempuan pertama di Amerika Serikat. Ia juga merupakan orang kulit hitam pertama dan orang pertama keturunan Asia Selatan yang terpilih menjadi wakil presiden. (*)
Humaira





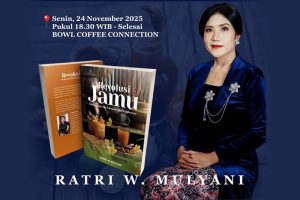
Terkait
Surat kepada Perempuan Pembela HAM yang Dipenjara
Perempuan Pembela HAM, Terdepan Berjuang untuk Keadilan di Tengah Ancaman yang Meningkat
PBB Bersiap Memilih Sekjend Baru, Kepemimpinan Perempuan Jadi Harapan