Pernahkah Anda membaca berita tentang pemerkosaan atau cerita persetubuhan? Jika ya, pernahkah Anda memperhatikan kalimat yang kerap digunakan oleh awak media atau beberapa penulis? Misalnya: “lelaki itu berhasil menodai adiknya sendiri”, “ia telah menyerahkan kesuciannya di malam pertama kepada lelaki yang sangat dicintainya”, “laki-laki itu sudah merenggut kehormatannya”, “tubuhnya kini tercemar akibat perbuatan ayah tirinya”, dan beberapa kalimat lain yang senada.
Apakah ukuran kesucian hanya sebatas keperawanan? Apakah perempuan yang sudah tidak perawan menjadi tidak suci lagi sebab ternoda, sehingga seluruh tubuhnya menjadi tercemar? Apakah dengan tidak perawan membuat perempuan tidak lagi terhormat? Lalu bagaimana dengan ibu yang sudah melakukan persetubuhan dengan bapak? Apakah dengan begitu ibu sudah kehilangan kehormatannya, sehingga kita tidak perlu lagi menghormatinya?
Lalu penggunaan kata ‘gagah’ untuk seorang lelaki dengan contoh kalimat: “lelaki itu berhasil menggagahi bunga berkali-kali” atau “berkali-kali bunga digagahi lelaki yang sama”, menunjukkan bahwa kekuasaan perempuan selalu di bawah laki-laki. Di mana gagah-nya seorang pemerkosa? Laki-laki yang melakukan pemerkosaan sejatinya seorang pengecut. Penakut. Sebab perbuatan memerkosa adalah upaya untuk menunjukkan kekuasaannya atas tubuh perempuan.
Dan ‘dibalik’ tindakannya adalah ‘ketakutan’. Takut dianggap lemah atau tidak berdaya. Anggapan-anggapan tidak selalu datang dari luar. Asumsi seperti itu lebih sering muncul dari dalam diri, mengaku sebagai suara hati yang sejati. Maka ketakutan itu terjadi akibat ketidak-mampuan melawan sisi gelapnya. Ketidakmampuan berdaulat atas dirinya menyebabkan seseorang mudah dikontrol oleh otak primitifnya, sehingga seluruh tubuhnya dengan mudah dikendalikan hanya dengan segumpal daging (kecil). Maka sekali lagi, di mana letak ‘gagah-nya’ seorang pemerkosa?
Kalimat-kalimat yang demikian jelas tidak adil bagi perempuan. Patrialkal, bahkan cenderung mengarah pada misoginis. Perempuan yang sudah menanggung beban psikologis dan beban sosial akibat pemerkosaan, masih pula dijadikan obyek (bukan subyek), hingga menyeret kaum perempuan secara umum. Pemilihan kata yang tidak tepat membuat tubuh perempuan seolah benda sehingga bisa tercemar atau dicemari, bisa ternoda atau dinodai. Seperti barang yang bisa diperlakukan sesuka hati.
Sayangnya masyarakat kita kurang kritis memandang istilah-istilah yang sudah banyak beredar. Tidak ‘mempertanyakan’ kembali kepatutannya. Yang sudah biasa digunakan dianggap umum dan yang umum dianggap lazim, padahal yang lazim belum tentu pantas. Mereka lebih suka mengekor tanpa memikirkan ke-tepat-annya. Mereka tidak berusaha mencari kata-kata baru sebagai ide baru yang lebih progresif menuju adil.
Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal budi. Yang menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek tidak hanya kaum lelaki, kaum perempuan sendiri punya potensi untuk melakukan itu terhadap kaumnya sendiri dengan memberi label-label tertentu yang bersifat negatif. Ada laki-laki yang suka (sadar atau tidak) menindas perempuan, ada perempuan yang mengamini penindasan sebab menempatkan dirinya di posisi yang lemah sebagai kodrat.
Tentu hal itu disebabkan adanya pendidikan yang salah, yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang tradisi patriarki yang sudah terkonstruksi dalam pandangan masyarakat. Maka yang patut dilawan bukan manusianya, melainkan cara berpikirnya. Di sinilah pentingnya peran perempuan, sebagai calon ibu yang akan mendidik generasi-generasi baru yang akan membawa perubahan. Sebab ibu adalah guru yang pertama, yang mendidik kita sejak dalam kandungan.
Siapa pun diri kita, apa pun latar belakang kita, layak dihormati dan dicintai sebagai manusia. Sebab manusia diciptakan dari rasa cinta, maka hakekat manusia adalah mencintai …
*Sumber: Catatan Tari Adinda





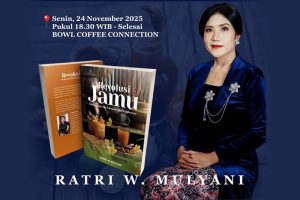
Terkait
Surat kepada Perempuan Pembela HAM yang Dipenjara
Perempuan Pembela HAM, Terdepan Berjuang untuk Keadilan di Tengah Ancaman yang Meningkat
PBB Bersiap Memilih Sekjend Baru, Kepemimpinan Perempuan Jadi Harapan