Apa jadinya jika penjual jamu kesuburan justru tak kunjung hamil? Di Kota Solo, tempat interaksi tetangga kadang lebih intim dari pasangan suami istri sendiri, situasi ini bukan sekadar kejanggalan. Ini bahan gunjingan. Judul Cocote Tonggo yang berarti cibiran tetangga—bukan sekadar tempelan: ia adalah jantung dari seluruh cerita, sekaligus kritik halus (tapi menyengat) tentang betapa tubuh perempuan, terutama rahim, belum pernah benar-benar menjadi milik pribadi.
Disutradarai oleh Bayu Skak dan diproduksi oleh Tobali Film, film ini mengusung kisah pasangan penjual jamu kesuburan di Solo, diperankan Dennis Adhiswara dan Ayushita yang justru tengah menghadapi ironi besar: mereka belum juga dikaruniai anak. Di sinilah komedi dan tragedi mulai bercampur. Sebab di balik ramuan jamu yang mereka racik, dan doa-doa yang diucapkan pelanggan, ada luka personal yang tak bisa diredam oleh kunyit asam atau godokan daun sirih.
Komedi, Kritik, dan Kehidupan Sehari-hari
Bayu Skak kembali memotret kehidupan masyarakat Jawa dengan pendekatan khasnya: ringan, kocak, tapi menggigit. Cocote Tonggo menyuguhkan tawa lewat situasi sehari-hari yang begitu akrab. Omongan tetangga jadi pemandangan yang tidak asing, apalagi di kota seperti Solo, di mana kedekatan sosial sering tak mengenal batas.
Dialog-dialognya hidup, bahkan kadang menyakitkan, dialog yang bukan sekadar lelucon, tapi pengingat pahit tentang betapa cepatnya masyarakat melompati empati dan langsung ke penghakiman.
Dennis Adhiswara dan Ayushita memerankan pasangan yang penuh kontras namun saling mendukung. Chemistry mereka kuat: sang suami yang mencoba tetap kocak walau batinnya remuk, dan sang istri yang terus berusaha menahan tangis sambil tersenyum. Karakter pendukung seperti Asri Welas dan Furry Setya menambah warna dengan akting yang luwes, satir, dan sekaligus menyentuh. Mereka bukan hanya tetangga bawel, tapi simbol dari suara masyarakat: sok tahu, sok peduli, tapi kadang menyakitkan.
Kritik Feminis: Rahim Sebagai Ruang Komunal
Di balik semua kelucuan, Cocote Tonggo menyimpan kritik feminis yang sangat tajam: tubuh perempuan, terutama rahimnya, telah lama diklaim oleh masyarakat sebagai urusan bersama. Karakter istri dalam film ini harus menanggung bukan hanya kegundahan pribadi, tapi juga tekanan sosial yang terus menginterogasi tubuhnya, seolah ia wajib menyubur demi menenangkan keresahan kolektif.
Simone de Beauvoir pernah menulis dalam The Second Sex: “Perempuan tidak dilahirkan, tetapi dijadikan.” Dan film ini menunjukkan betapa perempuan terus “dijadikan”, menjadi istri yang ideal, menjadi rahim yang produktif, menjadi simbol keberhasilan rumah tangga.
Judith Butler dalam Gender Trouble mengatakan bahwa tubuh perempuan adalah hasil konstruksi sosial. Dalam konteks film ini, kita melihat bagaimana rahim perempuan menjadi ruang yang bisa dikomentari siapa saja: dari tetangga, mertua, hingga pelanggan jamu. Bahkan sang suami, meski tidak secara langsung disalahkan, tetap tidak mengalami beban sosial serupa.
Ketubuhan perempuan dijadikan arena tafsir kolektif. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi si suami. Tidak ada ruang untuk kemungkinan lain. Yang ada hanyalah satu narasi tunggal: kalau belum punya anak, maka pasti salahnya di pihak istri.
Sara Ahmed, dalam Living a Feminist Life, menggambarkan bagaimana perempuan harus “menanggung kebisingan sosial” terhadap tubuhnya sendiri. Dan itulah yang dirasakan karakter Ayushita. Setiap doa, saran, sindiran, bahkan sapaan ramah, menyimpan tuntutan: “kapan ngisi?” pertanyaan yang terlihat ringan, tapi menyayat.
Menertawakan Luka, Merawat Refleksi
Cocote Tonggo adalah film yang membuat kita tertawa sambil mengernyit. Ia menyajikan realitas masyarakat Indonesia yang masih sangat terobsesi pada konsep keluarga ideal: suami, istri, anak. Tanpa anak? Maka rumah tangga dianggap belum lengkap, atau malah gagal.
Film ini menertawakan luka yang terlalu sering dianggap biasa. Lewat humor, Bayu Skak tidak melemahkan penderitaan, tapi justru menjadikannya pintu masuk untuk refleksi. Bahwa empati harus menggantikan komentar. Bahwa tubuh perempuan bukan ruang publik. Dan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk bayi.
Cocote Tonggo adalah film penting, bukan karena ia menawarkan drama besar atau konflik megah, tapi karena ia menyorot hal kecil yang sering tak dianggap masalah padahal bisa sangat menyakitkan. Ia mengajak kita untuk tertawa, iya. Tapi lebih dari itu, ia mengajak kita untuk berhenti menjadi bagian dari “cocote” itu sendiri.
Dan jika selama ini kita pernah ikut bertanya “kapan punya anak?”, film ini adalah undangan untuk diam, mendengar, dan mulai belajar memahami bahwa rahim bukanlah milik umum, dan kesuburan bukan ukuran nilai seorang perempuan. (*)
Milla Joesoef





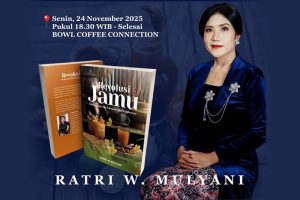
Terkait
Surat kepada Perempuan Pembela HAM yang Dipenjara
Perempuan Pembela HAM, Terdepan Berjuang untuk Keadilan di Tengah Ancaman yang Meningkat
PBB Bersiap Memilih Sekjend Baru, Kepemimpinan Perempuan Jadi Harapan